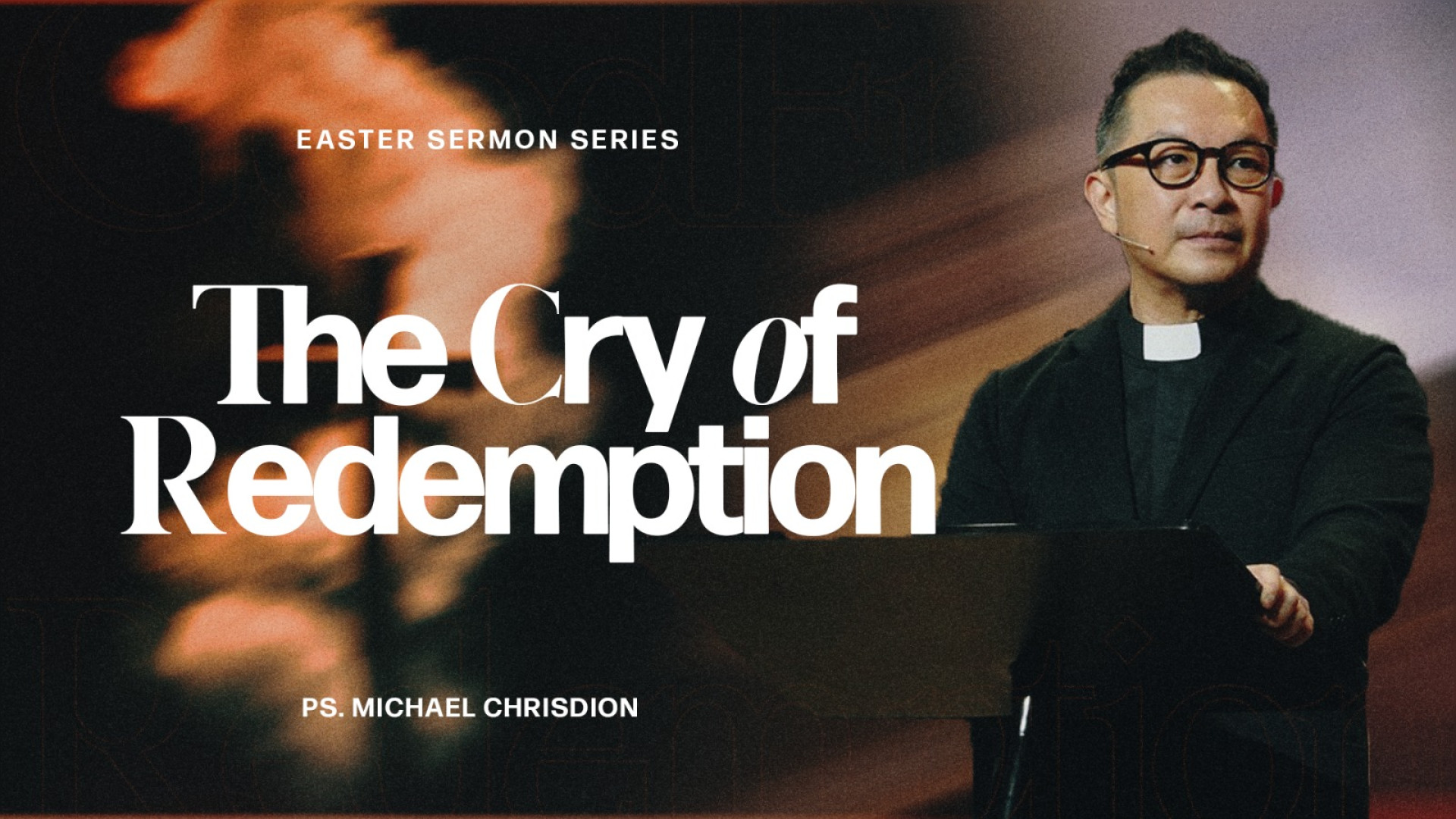
Kita bisa berkata bahwa ini adalah Jumat Agung karena Yesus mengalami kehinaan yang paling dalam. Kita menyebut hari ini Good Friday justru karena Yesus mengalami hal yang paling buruk. Dan hari ini, kita akan membahas The Cry of Redemption—seruan penebusan.
Bacaan: Matius 27:45-50
27:45 Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga.
27:46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
27:47 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Ia memanggil Elia."
27:48 Dan segeralah datang seorang dari mereka; ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum.
27:49 Tetapi orang-orang lain berkata: "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia."
27:50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.

Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan: Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, "Why, God? Why me?" “Mengapa aku? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?”
Pertanyaan itu bisa muncul saat kehilangan orang yang kita cintai—entah itu pekerjaan, pasangan hidup, atau bahkan ketika menerima vonis penyakit berat. Dalam saat-saat seperti itu, kita merasa sendiri. Terabaikan. Maka dari itu muncul pertanyaan: "Why, God?"
Namun hari ini kita mendengar sebuah pertanyaan yang mengejutkan dunia—keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib: "Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Yesus yang penuh kuasa. Yang menyembuhkan orang sakit, yang meredakan badai hanya dengan satu kata: "Tenanglah!" Dan seluruh angin serta ombak tunduk kepada-Nya.
Kini, justru Ia berseru dalam kesakitan dan keterpisahan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kayu salib?
Dalam satu kalimat itu tersimpan misteri terbesar sekaligus kabar baik bagi kita semua. Jika pernah muncul keraguan: "Apakah Tuhan benar-benar peduli pada penderitaanku?" Hari ini, kita menemukan jawabannya.
Ini bukan sekadar kisah Jumat Agung seperti biasa. Ini adalah kisah kasih yang terdalam, pengorbanan yang terbesar, dan harapan yang paling nyata untuk hidup kita.
Saya akan membahas tiga hal:

THE CRY (SERUAN-NYA)
Mari kita baca bersama Matius 27:46. Di sana dikatakan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring. Kata aslinya di sini bukan sekadar "berseru." Kata itu jauh lebih kuat. Artinya adalah berteriak—bahkan menjerit sambil menangis.
Bayangkan dengan jelas situasinya: Yesus, Sang Juruselamat, berteriak, menjerit, dan menangis di atas kayu salib. Ia tidak terlihat tenang. Ia tidak terlihat keren. Ia tidak tampak heroik. Yesus kelihatan sangat rapuh, seakan kehilangan kendali. Ia tampak putus asa, dan bahkan terlihat seperti menyerah.
Perhatikan apa yang dikatakan-Nya: "Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Seolah-olah Yesus berkata, "Tuhan, Engkau mengecewakan Aku. Engkau meninggalkan Aku sendiri."
Ini mungkin mengejutkan bagi kita. Tapi justru di sinilah letak satu fakta apologetika yang sangat penting. Para ahli sejarah—bahkan yang sangat skeptis terhadap Alkitab—tidak bisa mengabaikan bagian ini. Mereka mengatakan bahwa peristiwa ini pasti benar-benar terjadi. Mengapa?
Karena, kalau Injil hanyalah legenda atau karangan untuk mempromosikan agama, penulisnya tidak akan menampilkan tokoh utama iman Kristen dalam kondisi seperti ini. Biasanya, tokoh-tokoh besar agama akan digambarkan bijaksana, tenang, penuh wibawa, dan heroik.
Tapi di sini Yesus justru tampak sebaliknya—Ia terlihat hancur, emosional, rapuh. Maka para ahli pun berkata: "Tidak mungkin bagian ini dikarang." Cerita ini terlalu jujur, terlalu manusiawi, dan terlalu mengejutkan untuk dimunculkan jika hanya demi promosi agama. Tidak ada agama yang akan menciptakan Tuhan yang tampak rapuh, menjerit, dan merasa ditinggalkan. Justru karena terlalu jujur dan apa adanya, maka hal ini sangat mungkin merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi.
Dan ada hal menarik lainnya: seruan ini dicatat dalam bahasa aslinya, yaitu Eloi, Eloi, lama sabaktani atau Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Aram. Meskipun Injil ditulis dalam bahasa Yunani, kalimat ini dipertahankan dalam bentuk aslinya.
Mengapa? Karena ini adalah momen yang begitu mendalam. Para saksi mata tidak akan pernah melupakan teriakan ini. Mereka mendengarnya langsung. Kita pun hari ini tak boleh melupakannya.
Seruan ini bukan sekadar jeritan kesakitan, tetapi menjadi bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh menderita. Ia benar-benar mati. Kematian-Nya bukan sebuah kecelakaan. Ia menyerahkan nyawa-Nya—ini adalah penggenapan kasih Allah untuk menyelamatkan kita.
Jadi kalau disimpulkan: Kematian Yesus di kayu salib bukan legenda. Bukan mitos. Bukan dongeng. Melainkan fakta sejarah yang memiliki bukti nyata.
Jangan berpikir bahwa karena Injil ditulis oleh orang Kristen, maka ceritanya otomatis bias. Faktanya, kematian Yesus juga dicatat oleh banyak tokoh non-Kristen, bahkan oleh musuh-musuh Kekristenan. Beberapa contohnya:
Artinya, penyaliban Yesus bukan hanya bagian dari doktrin iman Kristen. Ini adalah bagian dari dokumen sejarah dunia. Jadi jika hari ini kita datang merayakan Good Friday, kita tidak sedang merayakan sebuah mitos. Kita bukan sedang mencari inspirasi semata. Kita sedang memperingati suatu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Dan sejarah inilah yang mengubah hidup kita semua.

WHY (MENGAPA)
Seruan Yesus di kayu salib, "Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" bukan hanya jeritan kesakitan, tapi kutipan langsung dari Mazmur 22—sebuah mazmur nubuat yang ditulis Daud ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Coba perhatikan bagian-bagian dalam mazmur itu: "Semua yang melihat Aku mengolok-olok Aku… Mereka menusuk tangan dan kakiku… Mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku." Kapan Daud mengalami ini semua? Tidak pernah. Artinya, Mazmur ini bukan pengalaman Daud secara literal, melainkan nubuatan profetik—tentang Yesus.
Jadi, saat Yesus mengutip Mazmur ini, Dia sedang menunjukkan: “Inilah yang sedang terjadi—aku sedang menjalani penggenapan nubuatan ini.” Dia sedang menjalani eksekusi, bukan sekadar kematian tragis, tapi penghukuman. Tapi bukan karena kesalahan-Nya sendiri. Yesus dihukum sebagai substitusi—pengganti bagi saudara dan saya. Dia menanggung hukuman atas dosa kita.
Dan sebagai tanda nyata dari penghukuman ini, lihat apa yang terjadi dalam Matius 27:45: "Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga." Ini bukan sekadar fenomena alam. Dalam Perjanjian Lama, kegelapan adalah simbol penghakiman Allah (lih. Amos 8:9). Maka, ketika gelap turun saat Yesus disalibkan, itu menunjukkan bahwa hukuman Allah sedang dijatuhkan—bukan kepada kita, tetapi kepada Anak-Nya.
Inilah poin yang membuat budaya modern sulit memahami salib. Dunia tidak suka konsep penghukuman. Dunia ingin bebas dari rasa bersalah. Kita hidup dalam budaya postmodern—atau bahkan post-postmodern—yang mengatakan: “Kebenaran itu relatif. Kamu yang tentukan benar-salahmu sendiri. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah.”
Bahkan dalam versi "Kristen progresif", konsep salib dikritik sebagai bentuk “pelecehan anak secara kosmis.” Dunia keberatan dengan ide bahwa Allah menghukum dosa. Tapi justru karena Allah adil, dosa harus dihukum. Dan salib adalah bukti bahwa Allah tidak kompromi dengan kejahatan—Dia menjatuhkan hukuman, tapi bukan kepada kita, melainkan kepada Yesus.
Andrew Delbanco, seorang intelektual sekuler dari Columbia University, menulis bahwa ketika seseorang tidak lagi merasa bersalah atas kesalahan, itu berarti dia sudah kehilangan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia menjadi ‘Tuhan’ bagi dirinya sendiri. Maka, rasa bersalah—betapapun tidak nyaman—adalah anugerah. Itu adalah suara dalam hati yang berkata: “Aku butuh pengampunan. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri.”
Dan di sinilah salib menjadi pusat pengharapan kita. Karena salib mengatakan: ya, rasa bersalahmu itu nyata; ya, dosamu itu jahat; ya, penghakiman itu harus dijatuhkan—tapi salib juga berkata bahwa kasih Allah lebih besar. Penghakiman itu tidak dijatuhkan kepada kita, melainkan kepada Kristus.
Jadi jika kamu masih bisa merasa bersalah, itu adalah bukti bahwa Tuhan belum menyerahkanmu. Masih ada kasih karunia. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan selama salib Kristus masih berdiri sebagai bukti kasih dan keadilan Allah, maka harapan itu tetap hidup.

MY GOD (ALLAH-KU)
Kita sampai pada inti dari penderitaan Yesus, momen paling gelap di kayu salib. Yesus berseru: “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” Ini bukan sekadar jeritan fisik. Yesus sudah mengalami penyiksaan luar biasa—mahkota duri menusuk kepala-Nya, tangan dan kaki dipaku, lambung ditikam—tapi Dia tetap diam. Tidak ada keluhan. Bahkan ketika murid-murid-Nya meninggalkan-Nya, Dia tetap tenang. Namun pada saat ini, Yesus berteriak.
Kenapa? Karena ada penderitaan yang jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik atau pengkhianatan relasional. Penderitaan terdalam manusia adalah kehilangan kasih. Saat seorang sahabat, pasangan, atau orang tua berkata, “Aku tidak mau melihat kamu lagi,” itu menghancurkan hati kita. Tapi di salib, yang meninggalkan Yesus adalah Bapa surgawi-Nya sendiri. Itu bukan hanya kehilangan kasih biasa. Itu adalah pemutusan keintiman kekal antara Bapa dan Anak, kasih yang sudah ada sejak kekekalan (Yohanes 1:18).
Yesus mengalami keterpisahan mutlak dari Allah, dan itulah hakikat neraka—bukan sekadar api, tapi terputusnya relasi dengan Sang Sumber Hidup. Itulah hukuman dosa. Dan Yesus menanggungnya, bukan karena Ia berdosa, tapi karena kita yang berdosa.
Robert Murray McCheyne menggambarkan penderitaan Yesus seperti anak kecil yang melempar batu ke jurang dan menanti bunyi jatuhnya, tapi tidak ada suara—begitu dalam kesunyian dan keterpisahan yang Ia alami. Namun meskipun Yesus tidak mendengar suara dari surga, Ia tetap berseru, “Allah-Ku.” Kata “Ku” adalah bahasa perjanjian—covenant language—ungkapan kasih dan keintiman. Di tengah neraka sekalipun, Yesus tidak berkata, “Aku menyerah.” Dia tetap berkata, “Engkau adalah Allah-Ku.”
Itulah ketaatan yang sempurna. Yesus tidak taat hanya saat terang bersinar, tapi juga saat langit menghitam. Kasih-Nya tetap dinyatakan, meskipun kasih itu tidak Ia rasakan. Dan karena ketaatan itulah, kita diselamatkan.
Melalui salib, terjadi pertukaran ilahi:
Ilustrasinya seperti seorang veteran tua yang mengenakan medali kehormatan. Saat ditangkap polisi militer, mereka batal menangkapnya karena melihat simbol kehormatan itu. Demikian juga, ketika Bapa melihat kita yang percaya kepada Kristus, Ia melihat ketaatan Yesus di dada kita. Kita diterima bukan karena kebaikan kita, tapi karena ketaatan Kristus.

Lalu, mengapa Yesus mau mengalami semua ini? Mengapa Ia rela merendahkan diri, turun ke dunia, dan akhirnya disalibkan dengan cara yang begitu hina dan menyakitkan? Ia adalah Allah. Ia memiliki segala kemuliaan dan keindahan kekal. Ia tidak butuh manusia untuk menyempurnakan Diri-Nya. Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia agar eksistensi-Nya sah. Tidak ada satu pun alasan dari sisi diri-Nya yang menuntut Dia harus turun dan menyelamatkan kita. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang pantas membuat-Nya berkata, “Mereka layak diselamatkan.” Lalu mengapa Ia tetap melakukannya?
Jawaban yang paling mendasar adalah: demi kemuliaan Allah. Karena Ia ingin memuliakan Bapa. Yesus berkata dalam Yohanes 17:4, “Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya.” Salib adalah ekspresi ketaatan yang paling sempurna kepada kehendak Bapa. Dalam ketaatan itu, kemuliaan Bapa dinyatakan. Kasih, kekudusan, keadilan, dan belas kasihan Allah—semuanya berpadu secara sempurna di salib. Di sanalah Allah dikenal secara utuh.
Tapi ada satu sisi lain yang juga sangat pribadi dan menyentuh. Ibrani 12:2 berkata, “Yang dengan sukacita menghadapinya salib, dengan mengabaikan kehinaan, dan duduk di sebelah kanan takhta Allah.” Apa yang membuat Yesus rela? Apa yang menjadi “sukacita” yang membuat-Nya sanggup mengabaikan kehinaan salib? Sukacita seperti apa yang bisa menutupi penderitaan salib?
Jawabannya adalah engkau dan aku. Gereja-Nya. Kita adalah sukacita yang ada di hadapan-Nya. Kita, yang ditebus dan disucikan oleh darah-Nya. Kita, yang akan menjadi mempelai-Nya. Kita, yang akan bersama dengan-Nya dalam kekekalan. Itulah sukacita-Nya. Itulah alasan mengapa Ia tetap berjalan ke salib, walau tahu bahwa penderitaan menunggu. Ia tidak menyeret langkah-Nya. Ia tidak dipaksa. Ia rela.
Seperti kata Tim Keller yang sangat terkenal itu:
“Saya begitu berdosa sehingga Yesus harus mati untuk saya. Tapi saya juga begitu dikasihi sehingga Yesus dengan sukacita memilih mati untuk saya.”
Dia tidak hanya menanggung murka, tetapi juga menanggungnya dengan kasih. Dia tidak hanya taat, tetapi juga taat dengan sukacita. Dia tidak hanya menggenapi perintah, tetapi juga mengasihi kita dalam ketaatan itu. Dia rela ditinggalkan supaya engkau dan aku tidak pernah ditinggalkan. Dia rela mengalami keterpisahan dari Allah, supaya engkau dan aku dapat hidup dalam kehadiran Allah selamanya.

Karya penebusan Kristus di kayu salib adalah cerita tentang ketaatan Kristus kepada Allah, bukan tentang betapa kita pantas atau tidak pantas menerima pengorbanan tersebut. Ketika Yesus mati, Dia bukan hanya menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tetapi Dia menuntaskan kehendak Bapa-Nya—sebuah kehendak yang jauh lebih besar daripada sekadar perasaan atau kenyamanan manusia. Penebusan yang dilakukan Yesus di salib adalah tentang pemulihan hubungan antara Allah yang kudus dengan umat manusia yang berdosa, yang sangat memerlukan kasih dan anugerah-Nya. Yesus datang untuk menuntaskan kehendak Allah, dan bukan untuk memberi kita pusat perhatian atau menegaskan bahwa kita adalah pusat cerita-Nya.
Kisah Yesus di salib mengajarkan kita bahwa kita bukanlah pusat dunia ini. Dunia ini berputar bukan karena kita, tetapi karena Allah dan karya penyelamatan-Nya melalui Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan umat-Nya, bukan untuk menjadikan umat-Nya sebagai pusat perhatian, melainkan untuk mengarahkan kita kepada kemuliaan Allah. Saat kita menatap salib, kita dipanggil untuk mengenali bahwa semua yang terjadi di sana adalah untuk memuliakan Allah, yang telah merancang penebusan ini demi kemuliaan-Nya.
Jadi, ketika kita merayakan penebusan Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa kisah ini adalah kisah yang lebih besar dari kehidupan kita. Ini adalah kisah tentang Allah yang mengasihi dunia-Nya dengan cara yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, tetapi kita terima dengan syukur dan iman. Kita tidak ada dalam kisah ini sebagai pusat cerita, tetapi sebagai bagian dari umat yang dipilih untuk menikmati kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus.
Maka ketika kamu merasa seolah-olah hidupmu hancur, ketika kamu merasa seperti ditinggalkan oleh dunia, ditolak oleh manusia, atau bahkan tidak sanggup merasakan kehadiran Tuhan, ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dulu ada di sana. Dia sudah berjalan melewati lembah kekelaman itu dan Ia tidak menyerah. Dan karena Dia tidak menyerah, kamu bisa berharap. Karena Dia menang, kamu bisa berdiri. Karena Dia disalibkan, kamu diampuni. Karena Dia ditinggalkan, kamu diterima. Karena Dia mati, kamu hidup.
Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan salib ini? Apa yang akan kamu lakukan dengan kasih yang begitu radikal ini? Kiranya kita semua tidak hanya sekadar tahu, tapi benar-benar percaya dan hidup di dalam kasih Kristus. Bukan dengan perasaan bersalah, tapi dengan kekaguman dan ucapan syukur. Bukan dengan kelelahan mencoba membalas, tapi dengan ketulusan menyerahkan diri.
Mari kita terus menatap salib itu. Mari kita kembali ke Injil itu, setiap hari. Biar penderitaan-Nya menjadi kekuatan kita. Biar kesetiaan-Nya menjadi inspirasi kita. Biar kasih-Nya mengubah hati kita.
Dan ketika kita melayani, mengasihi, bekerja, dan berdoa, biarlah semua itu lahir dari satu pengakuan: bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan diri-Nya bagi kita. Di situlah pengharapan kita. Di situlah kekuatan kita. Di situlah hidup kita.

STOP & REFLECT
Apakah kita masih gentar menghadapi dosa seperti Allah yang menggelapkan langit demi menghakimi dosa itu? Atau mulai menganggap dosa sebagai hal kecil yang bisa ditoleransi?
Apakah kita masih berkata "Allah-Ku" di saat tidak ada jawaban doa dan semua terasa hening? Atau hanya menyebut-Nya Tuhan saat hidup terasa nyaman?
Yesus tidak ragu membayar harga tertinggi di salib. Apakah hidup kita mencerminkan betapa mahalnya karya penebusan itu? atau masih jadi tanda tanya besar di hadapan-Nya?
ORANG BERINJIL
Menyadari bahwa Yesus berteriak dan menangis di salib agar saat berteriak dan menangis mereka tidak melakukannya dalam keputusasaan tapi dalam pengharapan.
Mempercayai bahwa mereka berdiri di hadapan Allah bukan karena ketaatan mereka kepada-Nya, namun karena ketaatan Kristus yang sempurna kepada Bapa-Nya.
Tidak narsis karena Yesus tidak mati agar mereka menjadi pusat cerita namun mereka dilibatkan dalam cerita-Nya yang kekal-cerita tentang kasih dan kemuliaan Allah.